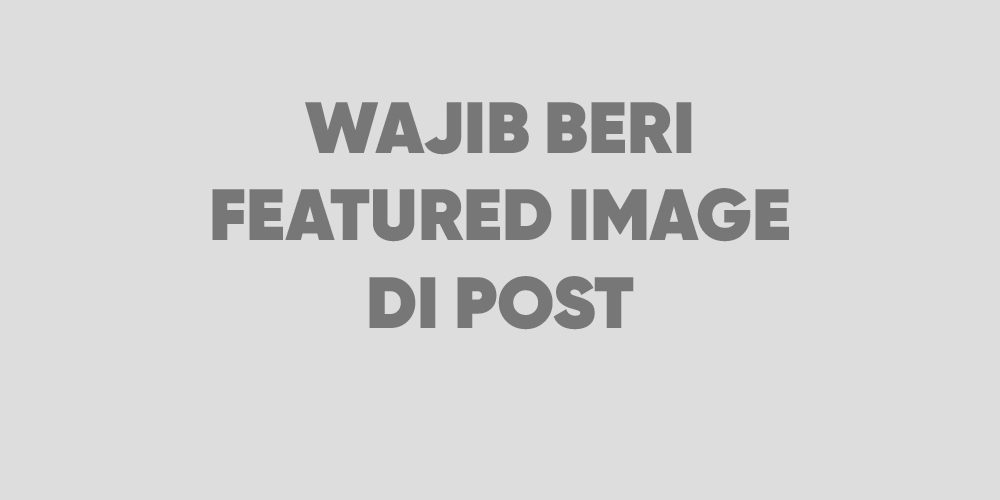Tahun 1963, Soekarno melalui Keputusan Presiden RI No. 169 Tahun 1963 menetapkan tanggal 24 September sebagai hari tani yang berangkat dari momentum lahirnya UU Pokok Agraria Tahun 1960. UU PA adalah kemenangan bagi rakyat tani Indonesia, dengan diletakkannya dasar-dasar bagi penyelenggaraan landrefrom, agar rakyat tani dapat membebaskan diri dari macam bentuk penghisapan menusia atas manusia dengan alat tanah, sehingga melempangkan jalan menuju k earah masyarakat adil dan makmur. Kini setelah 61 Tahun berlalui sejak lahirnya UUPA, cita-cita itu tak kunjung diwujudkan.
Pada Masa Orde Baru, UUPA disingkirkan dengan diterbitkannya berbagai Undang-undang sektoral bidang sumber daya alam, seperti UU No. 5 /1967 tentang Kehutanan dan UU No. 11/1967 tentang Pertambangan yang mengeksploitasi sumber daya alam secara massif. Paska Orde Baru tumbang, negara masih memfasilitasi pengerukan sumber daya alam oleh korporasi melalui UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 18/2004 tentang Perkebunan, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan. Pemerintah juga menggaungkan penggantian atau revisi UUPA, yang pertama dilakukan melalui RUU Sumber Daya Agraria, dan kedua melalui RUU Pertanahan. Meski kedua RUU ini tidak berlanjut, tetapi pemerintah berhasil memangkas prinsip-prinsip dan filosofi UUPA ke dalam sepasang Undang-undang predatorik yakni UU Mineral dan Batubara dan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Keluarnya kedua Undang-undang ini didahului dengan upaya sistematik oligarki membungkam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Paska keluarnya UU Cipta Kerja, pemerintah terus merangsek ruang-ruang hidup rakyat dengan pembangunan-pembangunan proyek infrastruktur termasuk yang berada dalam kerangka Proyek Strategis Nasional, proyek-proyek Food Estate, kepentingan umum, kawasan strategis nasional hingga Kawasan Ekonomi Khusus. Kantor-kantor LBH-YLBHI melaporkan pelanggaran-pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam proses pembangunan tersebut, di antaranya yang terjadi di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah dan Bitung, Sulawesi Utara. Masyarakat yang protes terhadap pembangunan tersebut disikapi secara amat represif.
Upaya pemerintah melapangkan jalan bagi investasi dengan mengabaikan segala pertimbangan pertimbangan keadilan lingkungan, keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Hal ini berimplikasi pada penyempitan ruang hidup petani dan ancaman terhadap ekologi yang kian serius, meningkatnya kekerasan, dan kriminalisasi terhadap petani. Sementara di tingkat birokrasi, korupsi sumber daya alam akan semakin menebal.
Sementara itu Presiden Jokowi terus berjanji hendak menyelesaikan konflik agraria dan melaksanakan reforma agraria. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakannya yang justru melanggengkan konflik agraria, dengan terus diberikannya kemudahan-kemudahan perizinan bagi korporasi untuk menguasai tanah-tanah skala besar untuk perkebunan, tambang, hutan, maupun proyek-proyek infrastruktur, PSN melalui UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Pemerintah juga membiarkan aparat kepolisian dan militer menjadi pelaku atau pem-backing para perusahaan dan terus melakukan kekerasan kepada rakyat. Bahkan BPN malah mensertifikasi tanah-tanah TNI di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah dalam situasi konflik agrarian yang memanas. Padahal reforma agraria tidak akan berjalan kalau konflik agrarianya tidak diselesaikan.
Beberapa upaya penyelesaian konflik tanah yang digadang-gadang oleh pemerintah seperti Perhutanan Sosial pada kenyataannya tidak berhasil menyelesaikan masalah mendasar ketimpangan penguasaan lahan. Bahkan di wilayah-wilayah adat, para petani banyak menderita kerugian akibat Perhutanan Sosial karena tanah adatnya diambil untuk Perhutanan Sosial. Dalam wilayah adat model, ini menjadi penundukan diam-diam masyarakat adat oleh Negara. Sementara itu, hutan adat menjadi sangat sulit direalisasikan karena prosedurnya sengaja dibuat sulit. Perhutanan Sosial bahkan menjadi modus baru bagi perusahaan untuk memperluas penguasaan wilayah seperti yang terjadi di Jambi.
Konflik-konflik Agraria yang berlarut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang tidak meletakkan penyelesaian konflik sebagai agenda prioritas. Sementara pada tingkat wacana pemerintah berupaya memanipulasi keadaan itu dengan menggaungkan bagi-bagi sertifikat pada petani. Tentu ada kebijakan bagi-bagi sertifikat yang merupakah bagian dari redistribusi tanah seperti baru-baru ini dilakukan di Bandungan, Jawa Tengah. Perlu ditekankan bahwa Petani Bandungan telah berjuang selama 21 tahun, sudah memperoleh putusan pengadilan, dan sertifikasi adalah buah dari perjuangan itu. Penyerahan sertifikat sudah semestinya dilakukan dalam kerangka tanggung jawab negara. Maka, proses ini tidak dapat digeneralisasi. Tidak seluruh bagi-bagi sertifikat atas tanah pada petani dapat dibaca sebagai bagian dari Reforma Agraria.
Maka, pada momentum hari tani ini, para petani perlu menyadari ancaman perampasan tanah, lingkungan, dan ruang hidupnya. Namun demikian petani harus terus berjuang. Maka kemenangan hari ini adalah kemenangan bagi petani yang terus berjuang.
24 September 2021
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Kontak Person:
- Era Purnamasari
- Siti Rakhma Mary