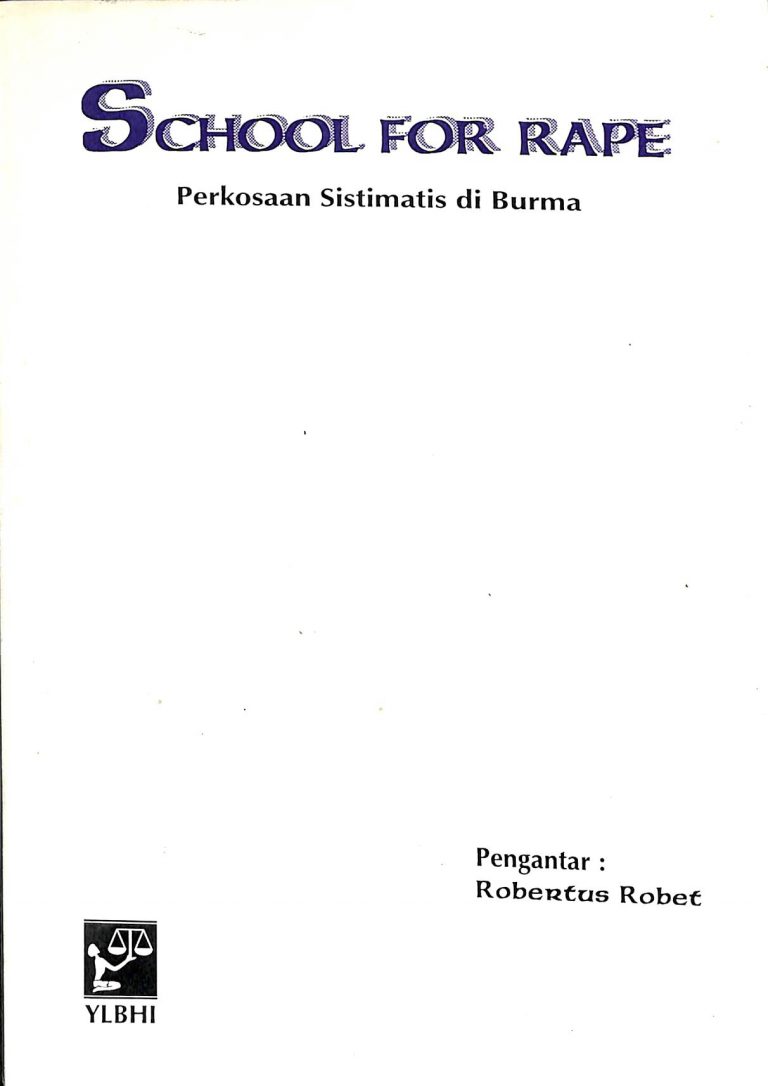Pada tahun 1998, Indonesia dipenuhi polemik tentang perkosaan massal terorganisir yang dilakukan oleh TNI terhadap perempuan etnis Tionghoa. Ternyata hal serupa juga terjadi di Burma, bahkan peperangan lain seperti di Sabine, Rwanda, dan Bosnia. Meski banyak yang menyangkal, mana mungkin negara melakukan hal keji seperti itu? Nyatanya hal tersebut ada.
Sayangnya, angka perempuan korban perkosaan di masa perang kerap terlupakan. Sebab, kekejian itu dilakukan secara sistematis dan tersembunyi. Terlebih, inventaris kerugian peperangan cenderung hanya berorientasi pada kerusakan materil seperti bangunan dan jumlah kombatan yang gugur.
Perkosaan terhadap perempuan di situasi perang merupakan hal yang lazim terjadi. Bahkan ia dianggap sebagai salah satu strategi militer. Perkosaan sebagai hal yang lazim dalam situasi perang disebabkan karena beberapa hal. Diantaranya karena berkembangnya asumsi tentang seksualitas laki-laki ketika dalam ketegangan, keyakinan bahwa tingginya aktivitas seksual laki-laki membangun kesan kemaskulinannya, dan pandangan bahwa kondisi perang bermakna kepemilikan perempuan berada di tangan laki-laki.
Fenomena tersebut tentu tidak lahir dari ruang kosong. Ia merupakan hasil strategi yang terstruktur dan sistematis. Kita mungkin terheran-heran bagaimana manusia terhadap manusia lain bisa berlaku kejam bahkan secara masif melembaga dalam sebuah angkatan bersenjata bela negara. Maka, buku ini menyajikan hasil investigasi dan analisis mengapa bisa kombatan melakukan perkosaan. Yang nantinya, agar lembaga-lembaga yang terlibat bisa dimintai pertanggungjawabannya, kombatan tidak lagi memiliki izin untuk memperkosa dan perempuan tidak akan lagi digolongkan sebagai korban kekejaman perang.
Sesuai judulnya, School for Rape, sebelum melaksanakan amanah bela negara, tentara dididik dengan sistem yang menjadikan mereka manusia tanpa ragu untuk memperkosa. Sistem tersebut diantaranya:
1) Usia prajurit di bawah 17 tahun. Mudanya mereka membuat berarti mereka belum memiliki pengalaman moral dan kemampuan kritis terhadap ideologi yang diberikan.
2) Tingkat pendidikan prajurit yang rendah. Mereka tidak memiliki pilihan dan kesempatan kerja, sehingga bergabung dalam militer adalah suatu alternatif.
3) Perlakuan sehari-hari. Prajurit dibiasakan untuk lapar, diberikan pakaian dan peralatan yang tidak layak dan diperlakukan sebagai budak sehingga hilang harga diri mereka hilang.
4) Isoalsi dari dukungan. Para prajurit dilarang berhubungan dengan keluarganya.
5) Teknik disipliner. Prajurit dididik untuk memberikan sanksi kepada sesama prajurit. Sehingga tidak ada rasa percaya diantara para prajurit melainkan kompetisi kekerasan.
6) Mereka juga diberikan alkohol dan obat-obatan terlarang yang membuat mereka lebih berani dan tidak terkendali dalam melakukan kekejaman.